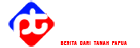JAYAPURA (PT) – Aksi penyelamatan lingkungan hidup dengan pendekatan budaya dipandang sebagai solusi tepat dalam mengatasi kerusakan alam di tanah Papua selama ini.
Pendekatan ini dinilai dapat menyentuh hati masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi kerusakan ekosistem dan keragaman hayati, terlebih menjaga kelangsungan hidup warga setempat.
Solusi itu pun menjadi rekomendasi dalam talk show bertajuk ‘Ekologi Papua dan Krisis Iklim’ dalam rangkaian diskusi School of Eco Diplomacy (SED) tingkat dasar yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu (13/10).
Diskusi ini, melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih (Uncen), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Forum Komunitas Papua-Rumah Bakau Jayapura dan Yayasan EcoNusa.
Menurut Pembantu Rektor III Uncen, Jhonathan Wororomi, kerusakan hutan yang berbuntut longsor dan banjir bandang tak hanya merusak ekosistem saja, melainkan menjadi petaka bagi kelangsungan hidup warga lokal.
Untuk itu, ia mengajak seluruh stakeholder untuk mengelola hutan dengan mengoptimalkan fungsi konservasi.
“Ketika hutan rusak, bukan hanya pohon yang hilang atau banjir (bandang), tapi juga proses interaksi lingkungan dan aspek sosial, budaya dan ini cukup complicated,” kata Jhonathan.
Salah satu warga Kampung Sereh yang terletak di kaki Gunung Cycloops, Yesaya Eluay menyebutkan rusaknya lingkungan di kawasan gunung itu, akibat aktivitas perkebunan yang berlebihan.
Umumnya warga berkebun di atas ketinggian 900 meter di permukaan laut.
Menurutnya, banyaknya pohon besar yang tumbang akibat penebangan liar, beralih fungsi menjadi perkebunan masyarakat.
Hal itu pun berdampak pada rusaknya sumber mata air.
Bahkan, dari 124 mata air yang mengalir sebelumnya, kini tersisa lima mata air saja.
“Dulu Cycloop dingin sekali, embunnya tebal membuat baju kita basah. Bahkan, jika kita masuk hutan harus pakai senter. Lihat pohon besar saja kami takut, namun saat ini itu semua tidak ada,” ungkap Yesaya.
“Cycloop juga sudah longsor. Banjir bandang Maret lalu menghancurkan rumah saya dan dua anak saya meninggal,” sambungya dengan sedih.
Yehuda Hamokwarong, Dosen Prodi Geografi Uncen, menilai banjir bandang Sentani, pada Maret 2019, ditengarai benturan budaya Tabi dan Lapago.
Suku Tabi memandang Gunung Cycloop sebagai tempat untuk berdoa dan memanjatkan syukur kepada Sang Pencipta.
Sebaliknya, Suku Lapago menempatkan cagar alam itu sebagai tempat mencari penghidupan.
“Pendekatan budaya adalah cara tepat untuk mengatasi itu. Misalnya, warga yang berkebun di atas gunung itu diarahkan agar berkebun di daerah penyangga,” kata Yehuda seraya mengajak kedua suku itu bekerjasama dalam pemulihan Cycloop.
Kasubbag Evaluasi Pelaporan Data dan Humas BBKSDA Papua, Paulus Baibaba menyebut kawasan Cycloops didiami oleh lima suku berbeda.
Menurutnya, pemerintah perlu mamahami perbedaan adat dan etika pemegang hak ulayat guna membantu program konservasi cagar alam tersebut.
“Generasi muda punya peran besar dalam pelestarian sumber daya alam serta advokasi masyarakat. Jika kita mencintai alam, maka alam akan lebih mencintai kita,” imbuhnya. (mt/sri)